Educated - Tara Westover
Beberapa tahun lalu saat iseng ngescroll-scroll timeline goodreads, mataku tertuju pada sebuah sampul buku yang terlihat menarik. Sampulnya didonimasi oleh gambar pensil dan kalau dilihat baik-baik akan tampak siluet seorang perempuan dan bayangan burung-burung terbang di sana. Di sampul itu juga tertulis judul Educated dan nama penulisnya Tara Westover. Beberapa tahun yang lalu aku masih gak terlalu berminat membaca buku non fiksi, tapi gara-gara melihat sampul buku itu aku pun membaca blurb buku itu dan rasanya menarik sekali. Tambahan lagi, buku itu terpilih sebagai Goodreads Choice Award tahun 2018 kategori non fiksi. Lalu awal April kemarin, buku ini akhirnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama.
Buku ini adalah buku memoar dari Tara Westover yang merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Masa kecilnya ia habiskan di pegunungan Idaho bersama 1 kakak perempuan, 5 kakak laki-laki, dan orang tua yang memiliki pandangan ekstrem terhadap dunia luar. Ayahnya tidak mempercayai pemerintah dan dokter. Anak-anaknya tidak diizinkan untuk pergi ke rumah sakit kalau mereka sakit atau terluka, ibunya lah yang bertanggung jawab untuk mengobati keluarga itu dengan obat-obatan herbal, yang kata Tara sebenarnya tidak banyak membantu mengurangi rasa sakit. Mereka sekeluarga pernah mengalami kecelakaan lalu lintas, sampai 2 kali, tapi mereka tidak pergi ke rumah sakit. Walau mereka terluka sampai berdarah-darah dan kepala ibunya terluka parah sampai wajahnya bengkak dan tidak bisa melihat dengan benar selama beberapa minggu, ayahnya tetap menolak pergi ke rumah sakit.
Tara dan kakak-kakaknya juga memiliki akta kelahiran yang tertunda, karena hal itu juga Tara dan keluarganya tidak tahu pasti kapan ia lahir. Selain itu, Tara dan saudara-saudaranya pun tidak memiliki kesempatan untuk duduk di bangku sekolah. Ayahnya menolak menyekolahkan anak-anaknya karena ia menganggap bahwa sekolah negeri adalah akal-akalan pemerintah untuk mencuci otak anak-anak. Ibunya akhirnya mengajari mereka di rumah, tapi sistem homeschooling itu tidak memberi mereka banyak ilmu karena sebagian besar waktu mereka digunakan untuk membantu ayah mereka bekerja di tempat barang rongsokan.
Waktu kecil hingga beranjak remaja, Tara menganggap perkataan ayahnya adalah kebenaran. Ayahnya adalah orang yang rajin bekerja (bahkan terlalu rajin sampai bisa dikatakan workaholic) dan taat sekali kepada Tuhan. Ayahnya sering memberi ceramah tentang hal-hal yang ditulis dalam Alkitab dan seringkali berkata bahwa hari kiamat akan segera tiba, maka ia pun sibuk menimbun persediaan makanan, bahkan menyimpan senjata agar keluarganya bisa bertahan pada hari kiamat.
Awalnya aku merasa mengikuti cerita Tara dalam buku ini seru sekali. Terlebih lagi Tara menceritakan sebuah kehidupan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tapi, semakin jauh aku menyelami dunia Tara, semakin aku merasa frustasi dengan kehidupan yang dijalaninya. Ia hidup di dunia yang sangat tertutup, "dilindungi" oleh kebenaran yang fana dari seorang ayah yang fanatik terhadap dunia luar yang makin lama semakin menunjukkan gejala paranoia yang parah. Belum lagi saat aku membaca bagian saat ia mengalami perundungan dari kakaknya, Shawn. Saat menceritakan tentang Shawn, aku pikir Tara beruntung karena punya kakak yang perhatian padanya. Shawn sering mengajaknya mengobrol, mengajarinya sedikit ilmu bela diri untuk melawan orang asing yang mau berbuat jahat, dan bersikap melindungi saat Tara beresiko terluka parah saat membantu ayahnya di tempat rongsokan. Tapi, ternyata Shawn adalah orang yang manipulatif. Lambat laun perlakuannya pada Tara semakin semena-mena dan kasar. Ia sering mengejek Tara dengan sebutan pelacur karena Tara mulai berdandan dan pergi bersama temannya, Charles. Ia juga sering melakukan perundungan fisik. Memelintir tangannya, mempermalukan Tara di depan umum, sampai memasukan kepalanya ke dalam toilet. Setelah itu ia meminta maaf dan berkata bahwa ia cuma main-main. Permainan macam apa yang sampai masukin kepala ke toilet, Bambang? Perundungan yang dilakukan Shawn dan tindakan keluarganya yang memalingkan muka sempat membuat Tara tidak berdaya.
"Hidupku dinarasikan untukku oleh orang lain. Suara mereka kuat, tegas, mutlak. Tidak pernah terpikir olehku bahwa suaraku mungkin bisa sekuat suara mereka."
Suatu hari, kakak Tara yang lain, Tyler, memberanikan diri untuk mengikuti tes ACT dan setelah ia lulus ia pun pergi dari rumah untuk belajar di Brigham Young University di Utah. Dari Tyler, Tara berkenalan dan jatuh cinta pada musik. Dari Tyler pula, Tara akhirnya memantapkan hati untuk mengikuti tes ACT dan akhirnya untuk pertama kalinya Tara duduk di ruang kelas pada usia 17 tahun. Aku membaca kisah Tara yang satu ini sambil ternganga lebar. Tara mempelajari semua pelajaran yang tertinggal, termasuk matematika yang isinya aljabar dan banyak sekali rumus. Buatku yang selalu langganan remedial matematika selama sekolah, Tara ini rasanya jenius sekali.. Tapi, kurasa orang tuanya pun jenius. Karena ada saat ketika saat Tara bingung dengan persamaan matematika, ia bertanya pada ayahnya dan ayahnya memecahkan persamaan itu dalam waktu singkat padahal ayahnya tidak pernah mengenyam pendidikan sampai lulus sekolah. Di titik ini aku merasa bahwa ideologi dan idealisme yang salah bisa membawa orang kepada suatu hal yang sia-sia.
Setelah masuk universitas, hidup Tara mulai berubah. Tara mulai bertemu dengan orang-orang yang sama sekali berbeda dan mempelajari hal-hal yang tidak pernah ia tahu sebelumnya. Saat awal masuk kuliah, Tara bertanya tentang Holocaust karena ia tidak tahu arti dari kata itu dan semua orang di ruang kelas memandang aneh dirinya, bahkan teman pertamanya menganggap Tara melontarkan lelucon yang tidak lucu. Padahal Tara benar-benar tidak tahu apa itu Holocaust. Pengalaman itu seperti memberi kesadaran bagi Tara, betapa buta dirinya terhadap dunia di luar pegunungan tempat tinggalnya.
Selama bertahun-tahun aku membaca buku, ada buku-buku yang membuatku speechless, entah saking bagusnya atau saking mindblowingnya. Tapi, buku ini benar-benar bikin aku gak tahu harus ngomong apa. Saat membuka halaman awal buku ini aku kira aku akan disuguhi dengan kisah yang membuatku terkagum-kagum sepanjang 490 halaman, tapi semakin jauh aku membaca semakin sering aku menghela napas. Dan fakta bahwa buku ini merupakan memoar, sebuah kisah hidup dari seseorang yang nyata, membuatku menghela napas lebih berat lagi. Walau Tara menjelaskan betapa berat ia menerima realita di hadapannya dengan realita yang selama ini ia ketahui dari ayahnya, aku tetap gak bisa membayangkan apa jadinya aku kalau berada di posisi Tara. Karena doktrin ayahnya yang takut pada dokter dan pemerintah, Tara tidak pernah divaksin, mati-matian menolak dibawa temannya ke dokter walau ia sakit maag parah, dan harus dibujuk beberapa kali oleh Uskup gerejanya untuk menerima bantuan pemerintah agar dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak tanpa harus kembali bekerja pada ayahnya yang membuatnya beresiko cacat seumur hidup atau bahkan kehilangan nyawanya.
Menyimak perjalanan hidup Tara dan mengetahui bahwa akhirnya ia bisa keluar dari kehidupan yang menjeratnya rasanya memberikan kelegaan yang aneh untukku. Aku suka dengan keberanian Tara untuk menentukan sendiri tujuan hidupnya setelah sekian lama ia mengalami perdebatan batin. Pada akhirnya, pendidikan yang ia tempuh membawanya jauh sampai ke Cambridge dan Harvard, membawanya menuju peradaban dan kebenaran dari pengetahuan sampai ia mendapat gelar PhD walau ia tidak punya ijazah SMA.
"Kita bisa menyebut pembentukan kepribadian ini dengan banyak istilah. Transformasi. Metamorfosis. Kepalsuan. Pengkhianat. Aku menyebutnya pendidikan."
Tapi, selain membawanya pergi jauh melintasi benua, pendidikan juga
membawa Tara pergi jauh dari keluarganya. Semakin ia mencari tahu,
semakin ia belajar, semakin banyak perbedaan persepsi yang terjadi
antara Tara dengan orang tuanya yang memiliki ideologi ekstrem. Berkali-kali Tara memvalidasi perasaan keluarganya terhadap dirinya, begitu pula sebaliknya. Tara tahu persis bahwa ayah dan ibunya mencintai anak-anaknya. Dan seperti kebanyakan orang tua, mereka berusaha mati-matian untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi, "yang terbaik" bagi orang tua belum tentu terbaik bagi anaknya. Yang menjadi ironi adalah orang tua Tara malah mengisolasi anak-anaknya dari dunia luar karena mereka pikir hal itulah yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi rasanya aku paham maksud Tara bahwa ia mencintai keluarganya tapi ia memilih untuk menjauh dari mereka.
"You can love someone and still choose to stay goodbye to them. You can miss a person everyday and still be glad that they are no longer in your life."
Aku juga merasa kagum dengan perjalanan Tara menempuh dunia pendidikan yang justru berawal dari perkenalannya dengan musik. Aku sedikit paham dengan rasa ingin tahu yang dimiliki Tara. Dari musik, ia belajar matematika untuk masuk universitas, kemudia ia berhadapan dengan fakta-fakta sejarah yang ia tidak tahu dan tertarik pada hal itu. Aku pun sering merasa tertarik mempelajari sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan background kuliahku atau penasaran dengan suatu hal baru yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Mungkin rasa ingin tahu ini yang merupakan intepretasi dari kalimat, "Kita bisa menjadi apa saja yang kita mau." Dalam interviewnya di channel youtube The Aspen Institute, Tara berkata,"You don't necessarily know where a love of something will take you, but you know that if you don't have any love for things you'll go nowhere." Kata-katanya itu mengingatkanku pada kata-kata Steve Jobs, "You can't connect the dots looking forward, you only can connect them by looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future."
Dan menariknya lagi, pendidikan yang ia tempuh tidak lantas membuat Tara menjadi orang yang merasa tahu segalanya. Benar bahwa pengetahuan yang ia dapatkan sudah melesat jauh sejak ia pertama kali duduk di ruang kelas. Tapi, begitulah cara mainnya. Semakin kita mencari tahu, semakin kita banyak belajar, semakin kita merasa bahwa pengetahuan ini bukan milik kita seorang. Untukku pribadi, semakin banyak aku belajar semakin aku merasa bodoh. Sebuah kontradiksi memang, tapi itulah yang aku rasakan. Semakin banyak pengetahuan yang aku serap semakin banyak juga ketidaktahuan yang terbentang di hadapanku. Ilmu pengetahuan itu tidak terbatas, ilmu pengetahuan itu terus ada dan terus berkembang. Siapalah kita yang merasa diri sok pintar.
"I don't think education is so much a state of certainty as it is a process of inquiry and I think an educated person is I don't think it's someone who can recite an army of facts and knows a lot of things, I think it's probably someone who has some flexibility of mind who's willing to examine their own prejudice who has acquired a depth of understanding that allows them to see the world from another point of view."
Dari perjalanan hidupnya, Tara juga memberi contoh untuk mengambil jeda sejenak. Pada Northeastern Commencement tahun 2019, Tara menyampaikan pidatonya yang berjudul The Un-instagramable Self. Ia menceritakan bahwa setiap foto setiap kisah yang kita bagikan di social media tidak merepresentasikan keadaan kita yang sebenarnya saat itu. Dalam pidato yang ia suarakan untuk para wisudawan itu, Tara berpesan untuk sejenak menoleh kepada sosok yang tidak kita bagikan di social media, sosok yang ia sebut "un-instagramable self".
"Take a moment to check in with your un-instagramable self and thank them for getting you this far, and for taking you the rest of the way."
Buku ini berhasil memberiku gambaran baru terhadap dunia luar yang selama ini tidak ku ketahui keberadaannya, memberiku harapan bahwa lewat pendidikan yang tepat manusia bisa berevolusi dari sisi IQ dan EQ, dan buku ini juga memberiku sudut pandang baru dalam memandang suatu hal terutama keluarga dan diriku sendiri. Educated jelas menjadi salah satu buku favoritku tahun 2021.
P.S: Untuk review buku lainnya bisa kalian baca di sini.
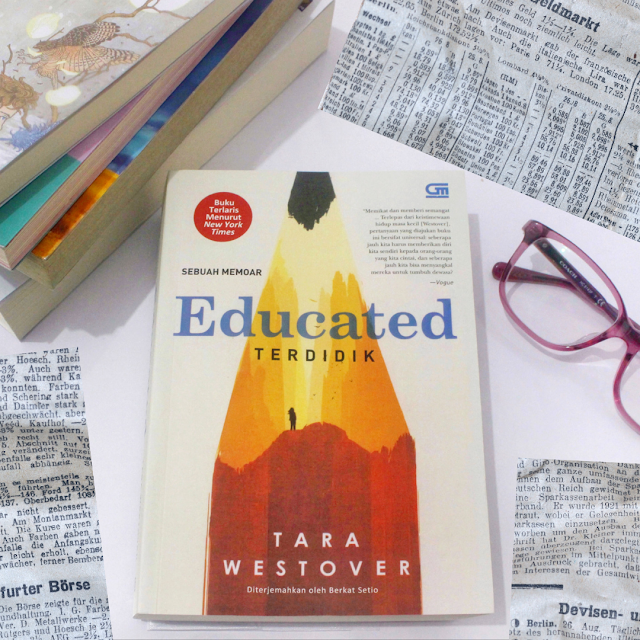


Comments
Post a Comment